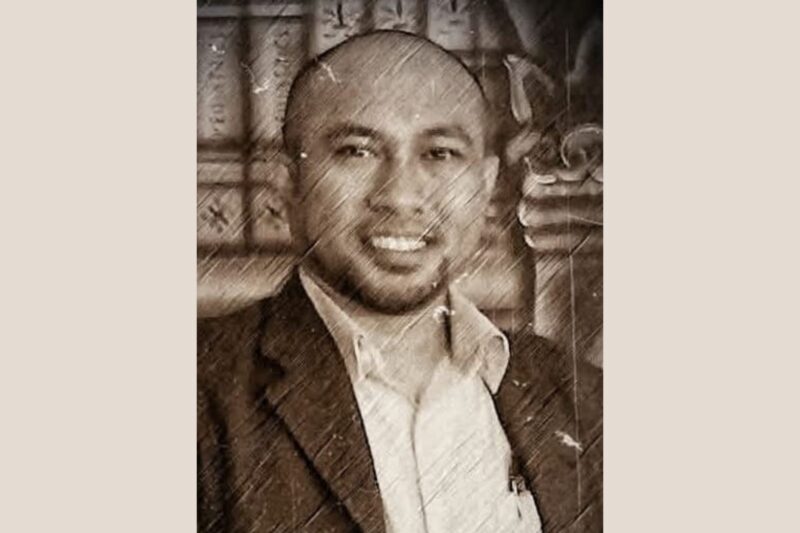Oleh: Ridwan Hanafi, Direktur Eksekutif Daulat Energi
“Jika bantuan luar negeri menghilang dan fiskal nasional dipangkas, transisi energi kita bisa kehilangan bahan bakarnya, secara harfiah dan metaforis.”
Dua pemimpin dunia Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai kembali masa kepemimpinan mereka. Meski berasal dari latar belakang politik dan budaya yang berbeda, keduanya langsung mengambil langkah yang serupa: efisiensi belanja negara.
Trump mengguncang Washington lewat pembentukan Department of Government Efficiency (DOGE) yang diketuai Elon Musk dan sederet executive order yang membuat dunia terpana, termasuk keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement 2015. Langkah ini praktis mengubur berbagai komitmen pendanaan transisi energi global, termasuk janji-janji dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP) kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Di sisi lain, Prabowo mengawali pemerintahannya dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Instruksi ini membawa angin segar bagi upaya pengetatan fiskal, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana nasib transisi energi nasional di tengah semangat efisiensi yang ketat?
Selama ini, transisi energi yang mengarah pada pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil dan peningkatan bauran energi terbarukan—dibiayai sebagian besar melalui komitmen internasional dan pinjaman lunak. Jika bantuan luar negeri menghilang dan fiskal nasional dipangkas, transisi energi kita bisa kehilangan bahan bakarnya, secara harfiah dan metaforis.
Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Justru, situasi ini membuka peluang untuk merumuskan ulang arah transisi energi yang lebih hemat, lebih cerdas, dan lebih kontekstual.
Baca juga: Belajar dari Skandal Pertamina, Padepokan Hukum Desak Reorganisasi PLN
Sektor energi nasional, khususnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara, harus menjadi contoh pertama dari efisiensi yang berorientasi masa depan. Banyak PLTU yang kini mengalami penurunan tingkat utilitas karena sistem kelistrikan semakin didominasi oleh pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). PLTU semacam ini seharusnya tidak lagi menerima alokasi anggaran operasional dan investasi yang sama seperti dulu.
Efisiensi tidak berarti anti-transisi. Justru, efisiensi adalah cara untuk menjaga agar transisi tetap berjalan meskipun dana semakin terbatas. Sehingga, beberapa prinsip yang harus diterapkan meliputi:
Pertama, Pengurangan OPEX dan CAPEX untuk PLTU berutilitas rendah, demi menyesuaikan dengan realita operasional saat ini.
Kedua, Optimalisasi stok batubara dan spare part, agar tidak terjadi pemborosan aset menganggur.
Ketiga, Realisasi proyek EBT yang berdampak langsung pada sistem, bukan sekadar proyek simbolik berbiaya mahal.
Transparansi dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek transisi, agar setiap rupiah benar-benar menghasilkan output energi yang bersih dan terjangkau.
Dari Gedung Putih ke Istana Merdeka, narasi efisiensi sedang menggema. Tantangannya kini, bagaimana Indonesia bisa menjalankan transisi energi dalam bingkai efisiensi, bukan dalam kerangka ketergantungan bantuan luar negeri.
“Efisiensi tidak berarti anti-transisi. Justru, efisiensi adalah cara untuk menjaga agar transisi tetap berjalan meskipun dana semakin terbatas”
Indonesia harus belajar merancang transisi energi berdasarkan kemampuan domestik, sambil tetap membuka peluang kolaborasi global yang adil dan saling menguntungkan. Efisiensi dan transisi bukanlah dua kutub yang saling bertentangan. Bila dikelola dengan benar, keduanya bisa berjalan seiring menuju sistem energi nasional yang tangguh, bersih, dan berdaulat.